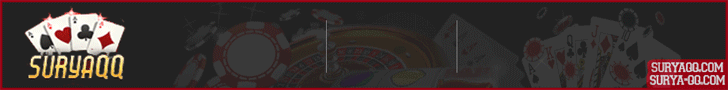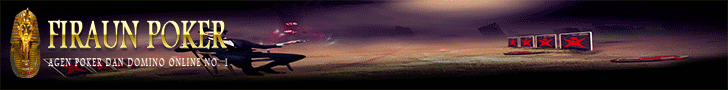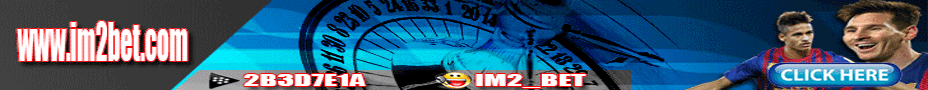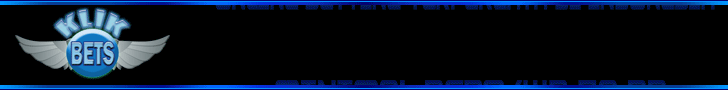“Buk” Tas sengaja kulempar ke atas kasur.
“Kalau tahu kayak gini ngapain juga gue dateng ke kampus, udah bermacet-macet ria dosen malah gak masuk, Ya Tuhan” Dengusku kasar.
Kubanting tubuh lelahku ke atas kasur kesayangan, kuregangkan seluruh sendi dan otot yang pegal karena menembus kemacetan pagi tadi.
Sambil memijit-mijit pelan kepalaku, aku menatap layar ponselku.
“Krek”
Terdengar gagang pintu depan dibuka oleh seseorang.
Malas menjalar di seluruh tubuhku, aku tidak memperdulikan siapa yang masuk ke dalam rumah.
Tidak lama kudengar bunyi tas dilempar seperti yang kulakukan sebelumnya.
Dengan badan yang pegal dan lelah, kupaksakan untuk bangkit melihatnya.
Disana aku melihat, seseorang yang amat aku cintai tengah terduduk di kursi meja makan, menunduk sambil sesekali meremas rambutnya sendiri.
“Loh Ayah udah pulang? Ini kan baru jam 11?”
Mendengar aku bertanya, ia mengangkat wajahnya dan tersenyum.
“Iya Ayah pulang cepet. Ibu mana? Kamu enggak kuliah?” Tanyanya dengan penuh kelembutan.
“Ibu jam segini biasanya lagi di tempat tante, ngerumpi. Dosennya gak masuk. Ayah mau makan? Biar aku bikinin”
“Tidak, tidak usah. Ayah masih kenyang” Jawabnya seraya bangkit dari kursi dan berjalan gontai menuju kamarnya.
Aku melihat sesuatu yang tidak wajar di raut wajahnya, dia terlihat sangat murung. Seseorang itu, seseorang yang mempertaruhkan tubuhnya di kehidupan luar yang kejam demi dapat menghidupi kami, menghidupi aku. Seseorang yang rela di sepertiga malamnya terbangun, berdoa menahan kantuk demi restu Tuhan untuk masa depan yang indah untuk anak-anaknya. Seseorang yang rela mengabaikan lelah di tubuhnya ketika melihat anaknya terkapar karena penyakit ringan, menggandeng atau bahkan menggendongnya, membawanya ke rumah sakit.
—
“Yah, ini aku bikinin teh manis, diminum aja dulu gak kalah enak kok sama buatan Ibu” Ucapku seraya tertawa cekikikan.
Dia membalikan tubuhnya yang sedang menatap pemandangan di luar jendela kamarnya.
“Iya, makasih yah, kamu bisa tolong jemput Ibu pulang? Bilang sama Ibu, ayah mau bicara” Wajahnya terlihat lesu, sambil sesekali menghela nafas dalam.
Aku bergegas ke luar kamar, sedikit mempercepat langkah kaki, sampai-sampai bertabrakan dengan adik perempuanku yang baru saja pulang dari sekolah.
“Buru-buru amat sih kayak lagi kebelet pup” Ucapnya meledek sambil mengelus lengannya yang tertabrak oleh tubuhku.
“Berisik lu, sana ganti baju, makan bikin sendiri aja ya”
Aku berlari menuju rumah tante yang berjarak tidak terlalu jauh dari rumahku. Pikiranku menerawang, apa yang terjadi? Apa yang ingin Ayah bicarakan dengan Ibu?
“Bu, Ayah nyariin tuh” Tegurku singkat.
Ibu bangkit dari duduknya dan berjalan menghampiri. Lalu kami berjalan tergesa bersama menuju rumah.
Ibu tidak membuang waktu dan langsung masuk menemui Ayah di kamarnya.
“Ada apaan sih?” Tanya adikku yang sedang berdiri di depan kulkas sambil memegangi jus di tangannya.
“Meneketehe” Ucapku ketus seraya meninggalkannya dan masuk ke dalam kamar.
Untuk kali pertama, dari dalam kamar aku mendengar keributan hebat di kamar Ayah dan Ibu. Adik berlari ke dalam kamarku, dia terlihat kaget dan ketakutan. Aku menyuruhnya untuk duduk di atas kasurku. Aku coba mengintip ke luar kamarku, aaah aku terlalu takut untuk melihat mereka. Kegaduhan itu, cacian dan makian itu, emosi-emosi yang mereka perdengarkan itu, membuat kami; aku dan adikku, merasa dalam keadaan sangat mencekam. Aku bersumpah, aku lebih berani mendengar suara kuntilanak tertawa ketimbang mendengar mereka saling mengadu urat. Aku benci kepada diriku sendiri, aku benci betapa pengecutnya aku memilih menahan diri di kamar dan tidak menemui mereka.
Kejadian itu berlangsung cukup lama, dan diakhiri dengan suara pintu yang terbuka dan suara isak dari Ibuku.
Aku ke luar, aku hampirinya, aku ingin bertanya, tapi sungguh tidaklah baik memotong tangis seseorang, kan?. Aku merangkulnya, kucoba memeluk tubuh seseorang yang kucintai sama seperti Ayah. Kepala Ibu terbenam di atas dadaku, dia terisak, dia memaki pelan. Aku tidak mendengar jelas apa yang dia ucapkan, suaranya amat parau.
“Bu, sudah, sabar, istighfar” Hanya itu yang sanggup kuucapkan.
Aku melihat adik mulai berani ke luar kamar dan menghampiri kita.
—
Setelah kejadian itu, berhari-hari aku melihat kedua orangtuaku saling diam. Ayah tidak pernah berangkat bekerja, Ibu tidak pernah memasak atau membantuku membereskan rumah.
Tidak ada lagi makan malam satu meja, tidak ada lagi menonton tv bersama sambil bercerita dan mendengar candaan renyah ala Ayah, tidak ada lagi sarapan pagi bersama dengan wejangan-wejangan ala Ibu, tidak ada lagi karaoke di rumah setiap hari minggu, tidak ada lagi bertengkar memperebutkan remote antara aku dan adik yang dilerai oleh Ibu maupun Ayah. Aku merasa sedang tidak rumah, aku merasa ini bukan rumahku.
Keadaan rumah tetap menyedihkan sampai pada suatu hari, aku kembali mendengar pertengakaran antara Ibu dan Ayahku.
“Praaang” Suara benda dilempar keras.
Suara tangis, teriakan, makian, sumpah serapah, semua aku dengar dengan jelas dari dalam kamar. Aaah, aku sudah terlalu lelah melerai mereka.
“Brak” Pintu kamarku dibuka dengan kasar oleh adikku.
“Kenapa?” Tanyaku dengan wajah terkaget-kaget.
“Ayah mau pergi” Jawabnya dengan airmata menggantung di kedua kelopak matanya.
Aku berlari ke luar kamar, kutemui mereka. Kulihat Ibu terduduk di sofa dengan menutup wajahnya menggunakan kedua tangannya menyembunyikan tangis.
Kugerakkan kepalaku ke kanan dan ke kiri mencari sosok Ayah yang aku cintai. Tidak ada.
Aku berlari ke kamarnya, kulihat dia berbenah koper, memasukkan baju-bajunya dengan sembarangan, kulihat tubuhnya bergetar menahan tangis dan emosi.
“Ayah mau kemana?” Aku tak sanggup lagi menahan tangis, airmataku tumpah mengaliri pipi yang sering dicubit manja oleh Ayah dan Ibu.
Dia hanya diam, sambil terus memasukkan baju-bajunya.
Aku terduduk dengan membenturkan lututku ke atas lantai.
“Ayah jangan pergi” Tangisku benar-benar pecah. Dadaku rasanya sesak. Nafasku seperti tersedat di tenggorokan. Aku merengek memohon untuk jangan ditinggalkan.
Ayah mengangkat wajahnya dan menatapku lesu. “Jaga adik, jaga Ibu, Ayah tau kamu lebih kuat bahkan lebih dari Ayah” Ucapnya singkat, dan berdiri membawa kopernya menuju pintu ke luar.
Aku masih terisak, terduduk, pikiranku buntu, aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan.
Sejenak setelah aku berpikir, aku bangkit dan berlari menuju dapur, aku mengambil sesuatu.
Aku segera berlari mengejar Ayahku yang baru sampai di pintu depan.
Aku mencegatnya di depan pintu.
“Stay or kill me” Ucapku seraya menyerahkan sebuah pisau dapur.
Ayahku terpaku, kulihat Ibu menghentikan tangisnya.
“Yah, stay here or kill me” Aku mengucapkannya sekali lagi.
“PLAK” sebuah tamparan keras mendarat di atas pipiku yang dialiri airmata.
Aku butuh beberapa detik untuk tersadar dari kesakitan yang menyerang kepalaku.
“Kalo Ayah mau pergi, bunuh aku, bunuh aku biar aku tidak merasakan sakit kehilangan Ayah” Aku mencoba sekali lagi memberikan pisau dapur ke tangannya.
“Ayah sama Ibu bukan lagi masa pacaran, ketika kalian ada masalah kalian bisa memilih pergi dan masalah selesai. Tidak, Yah. Sekarang kalian punya kita, punya aku dan adik.” Aku mencoba berbicara sejelas mungkin tanpa tersenggal-senggal karena tangis.
Ayah hanya diam. Dia menatap kosong ke arahku.
Setelah beberapa menit hanya terdiam, Ayah menubruk tubuhku dan meninggalkan aku yang terhempas ke dinding.
Dia pergi, dia melangkahkan kaki dengan tergesa meninggalkan rumah ini, meninggalkan aku, meninggalkan kami.