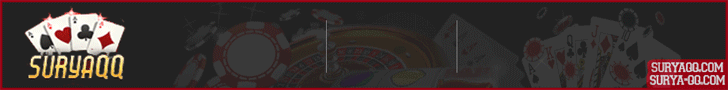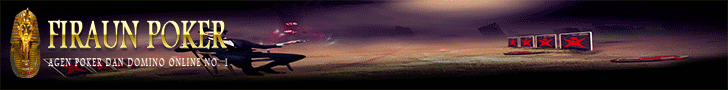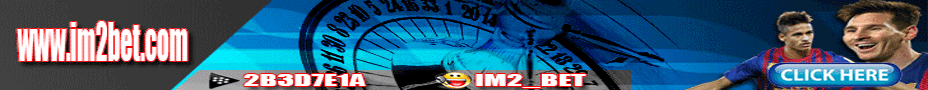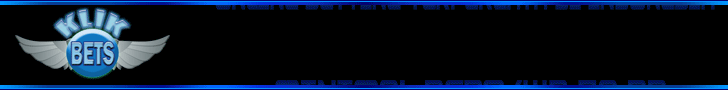Apa katamu!”
Dengan nada geram aku membentak. Dadaku bergelora menahan luapan emosi dan napasku memburu seperti kijang di padang rumput. Kepalan tanganku mengepal keras, seakan meremas hancur batu karang yang ada di lautan. Mataku menyalak serupa serigala di malam hari. Beruntung aku masih bisa menahan amarah yang melumat habis setiap darahku, mendidih bagai air yang dimasak dalam koali. Aku coba menenangkan diri.
“Sekali lagi aku tanya. Apa katamu tadi!”
“Renata, sudah SMU. Dia perlu biaya untuk bersekolah!”
Belinda menjawab tegas, sambil menatap wajahku dan saling bertatapan. Dari balik wajahnya ada sebersit ungkapan yang tak pernah dia ucapkan, ada sesuatu yang dia simpan selama bertahun-tahun.
Belinda adalah mantan istriku dan telah resmi bercerai lewat gugatanku di Pengadilan Negeri pada tiga tahun silam. Pernikahan kami kandas di tengah jalan sewaktu Renata, putri semata wayang masih duduk di bangku SD kelas enam. Mahligai rumah tangga kami pada awalnya sangat bahagia dan bisa dibilang pasangan yang sukses jika dibandingkan dengan sesama teman yang seangkatan ataupaun warga yang ada di seputaran lingkungan kami, karena bisa membangun berbagai usaha walaupun masih dalam kategori usaha kecil-kecilan.
Urusan rumah tangga sebetulnya adalah urusan yang sangat prinsip; untuk bisa tumbuh dan berkembang secara mandiri dan dewasa, namun siapa bilang tidak ada permasalahan. Setiap rumah tangga sudah pasti akan menemui segala masalah. Jika kita menerima dengan lapang dada, saling menghormati dan saling memaafkan, semuanya akan terkendali.
Namun bahtera rumah tangga kami kandas di seperempat perjalanan oleh karena campur tangan dari orangtua Belinda. Mereka tidak mau melihat aku dan Belinda bertengkar sedikit saja, Belinda akan dibela mati-matian oleh bapak dan ibunya. Sungguh suatu tindakan yang membuat aku tersinggung, sebab Belinda telah menjadi istriku maka otomatis segala sesuatu adalah menjadi tanggung jawabku, dan bukan lagi tanggung jawab mereka.
Hal inilah yang memicu retaknya kasih sayang dan rasa cinta yang selama itu kita pupuk sejak dari masa pacaran selama kuarng lebih lima tahun, Bagaikan membangun sebuah gunung es, dan bila tiba masanya maka ambruk dan meluluhlantakan segala cita-cita dan rencana untuk masa depan rumah tangga. Sudah berulangkali kuperingatkan kepada Belinda, namun semuanya ditepiskan dengan sikap acuh tak acuh, sebab dia lebih condong berpihak kepada orangtuanya ketimbang aku sebagai suaminya yang sah.
Dan pada akhirnya, aku harus mengambil sebuah keputusan berat kepada Belinda, memilih untuk mendengar segala suara dari orangtuanya yang notabene mempunyai harta kekayaan yang cukup terutama hasil perkebunan mereka ataukah mengikuti aku yang memulai kehidupan sejak dari nol. Keputusan terakhir jatuh ke Pengadilan Negeri dengan palu diketuk di atas meja hijau sebanyak tiga kali oleh Hakim Ketua, pertanda perceraian kita telah sah.
Dan sejak saat itu. aku menghilang dari kampung halamanku dan hanya berpamitan kepada ibuku yang sudah hidup menjanda, dengan pendapatan pensiunan PNS setiap bulan dan juga kepada putri tunggalku, Renata.
“Ibu, aku segera berangkat!”
“Tujuan kamu kemana, Rangga!”
“Jakarta, Bu. Aku ingin mengadu nasib di sana!”
“Nanti dicari alamat pamanmu…”
“Sudah ada padaku, Bu. Ibu jangan khawatir dengan keberadaanku di perantauan, aku hanya mohon Ibu ikhlaskan aku dengan doa!”
“Iya, kamu juga harus rajin berdoa dan taat beribadah, ibu akan selalu mendoakanmu, Rangga!”
“Ayah, ayah mau ke mana!”
“Ayah mau kerja di Jakarta, Nata, rajin-rajin ke sekolah ya, nak, nanti kalau ayah sudah bekerja dengan baik, ayah akan kirim uang buatmu!”
“Iya, ayah!”
Saat itu juga walau dengan berat hati untuk melangkah pergi, namun dengan tekad dan keyakinan bahwa aku harus keluar dari kemelut ini, jika tidak dan masih berdiam diri di kampung halamanku barangkali akan timbul hal-hal yang tidak diinginkan oleh semua pihak, terutama ibuku, anaku dan semua keluargaku.
Tiga tahun telah ku lewati, dengan harapan untuk melupakan semua masa lalu, yang pernah membuat aku terombang ambing dalam kemelut rumah tangga. Perlahan-lahan prahara itu telah sirna, ibaratnya sebuah jejak yang tertinggal di tepian pantai, ketika datang air pasang maka lenyaplah semua bekas. Bilur-bilur cinta telah sembuh terkikis oleh waktu yang berputar.
Setelah semalam aku tiba dari Jakarta melewati masa perjuangan untuk mengadu nasib selama tiga tahun. Pagi itu dari serambi rumahku aku melihat sebuah kantin makan, tak jauh dari seberang rumahku. Sebuah kantin untuk mencari dana dari perkumpulan ibu-ibu Gereja.
Kulihat ada beberapa teman lama yang duduk-duduk di kantin itu. Aku jadi tertarik dan ingin bergabung bersama mereka.
Sambil minum kopi dan makan pisang goreng disela-sela obrolan,
“Rangga, kamu kapan datang!” Ridwan sahabat lamaku
“Semalam, Wan, terlalu capek jadinya aku gak keluar rumah, langsung tidur aja”
“Kamu kelihatan gemuk, Rangga!” Sisco juga sahabatku
“Ah, biasa aja kok, Sis. Mungkin karena baru ketemu jadinya kelihatan aku agak gemuk!”
“Benar loh, Rangga, itu semuanya kan dari pikiran kita. Bila pikiran kita tenang maka nampak perubahan pada postur tubuh kita, tapi bila kita galau meen, kaya mayat hidup aja… Ha ha ha!” semuanya ikut tertawa.
Suasana di kantin itu cukup ramai dan semua teman-teman juga suka bercanda dengan obrolan lucu mereka.
Tanpa sepengetahuanku, ternyata di dapur sana ada beberapa ibu-ibu yang menjagai kantin hari itu ternyata salah satu adalah Belinda, mantan istriku. Mungkin saja, kalau aku sudah tahu duluan bahwa Belinda ada di kantin itu, gak bakalan aku datang. Tapi sudah terlanjur. Ketika aku baru mengetahui setelah kepergok aku di belakang untuk meminta tambahan pisang goreng, aku menjadi grogi dan hampir salah tingkah jadinya, Belinda hanya menatap sinis padaku. Kupalingkan wajah dan hendak berlalu.
“Aku tahu kamu tiba semalam, Rangga,”
Langkah kakiku tertahan sejenak, lalu memberanikan diri menghadap Belinda.
“Aku perlu bicara denganmu, Rangga..!” lanjutnya
“Emm, maaf..cerita kita telah usai. Maaf, aku tak ada waktu bicara denganmu!” jawabku perlahan
“Kamu ternyata laki-laki pengecut, laki-laki yang tidak bertanggung jawab!!”
“Apa katamu!!”
—
“Belinda, mari kita duduk dan bicara baik-baik!” Sambil menarik kursi dan diikuti pula Belinda
Teman-teman yang telah mengetahui aku dan Belinda telah mulai beradu mulut, mereka pun menyingkir keluar sambil duduk di balai-balai bambu membiarkan kita berdua saling bicara di dapur. Suasana yang hendak memancing emosiku tadi, perlahan-lahan reda setelah aku bisa cepat menguasai keadaan.
“Aku tahu, Renata sudah masuk SMU. Dia telah tumbuh menjadi seorang gadis dan perlu biaya untuk bersekolah dan segala kebutuhan lainnya!”
“Rangga, lalu kenapa sampai saat ini kamu tidak pernah mengirimkan uang buat sekolahnya, hak asuh anak ada padaku, tetapi kamu yang paling bertanggung jawab untuk membiayai sekolahnya!”
“Benar Belinda.. Aku tahu tanggung jawabku. Tetapi apakah mungkin selama ini dia pernah menjerit-jerit karena kehabisan uang,!”
“Dan apakah mungkin selama ini Renata pernah mengeluh karena ketidakcukupan segala kebutuhannya, ataukah engkau sendiri yang meminta aku…”
“Aku tidak meminta apa-apa darimu, Rangga!” Belinda memotong
“Lalu kenapa kamu sendiri yang meminta aku segala”
“Aku hanya mengingatkan kamu, Rangga!”
“Cukup. Belinda. Tak perlu kamu mengingatkan aku, karena kita tidak ada apa-apanya sekarang, sebab cerita tentang kita telah musnah dan lenyap, tak ada lagi yang tersisa antara kau dan aku!”
Belinda tertunduk diam. Dalam hati kecilnya masih ada rasa cinta terhadap Rangga, namun Rangga telah mengambil sebuah keputusan yang tepat dan menceraikannya. Belinda tak bisa berbuat apa-apa.
Sebetulnya perkawinan antara aku dan Belinda, tidak pernah direstui oleh kedua orangtuanya. Belinda menyadari akan hal itu. Dia juga sayang kepada orangtuanya, walaupun Belinda sangat mencintai aku. Dia tidak mau dianggap sebagai anak yang tidak berbakti kepada orangtua. Belinda hanya pasrah kepada nasibnya.
“Dari sinar matamu, aku bisa membaca kedalaman hatimu, engkau masih menyimpan sisa cinta buatku”,
“Siapa sudi”, sergah Belinda dengan suara mulai serak
“Jangan bohongi dirimu sendiri, masih belum cukupkah dahulu engkau lebih memilih mencintai ayah ibumu, memilih harta kekayaan mereka, memilih mereka yang tidak senang kepadaku dan sekarang engkau menyangkali dirimu sendiri untuk kesekian kali lagi untuk menyisakan sebuah arti cinta padaku!!?”
Saling Membisu, Belinda tertunduk lalu menangis sesunggukan, Bahunya nampak naik turun menahan isaknya, yang terdengar hanya suara hidungnya yang tersumbat dengan ingus.
“Hari ini aku datang hanya buat Renata dan ibuku, mereka adalah orang yang kucintai dalam hidupku!”
“Hari ini aku datang secara khusus buat Renata seorang. Bila kau ingin mengetahui yang sebenarnya bahwa aku tidak pernah mengirimkan uang kepada Renata. Sebab aku hanya menitipkan sebagian kecil uang buat keperluan kecil buat Renata dan ibuku, tetapi hari ini aku datang dan akan memberikan seluruh kekayaanku, hasil jerih keringatku kepada Renata seorang untuk dia membangun sebuah istananya, tetapi tidak untuk kamu Belinda!”
“Dan kamu ingin tahu yang sebenarnya tentang aku, aku meninggalkan kamu karena aku ingin mengejar mimpi yang kemarin tetinggal di pucuk prahara, di dasar jurang yang menganga, di atas tebing-tebing yang runtuh, oleh karena kesombongan dan keegoisan kalian, terutama orangtuamu!”
Tiba-tiba dari balik pintu, tanpa sepengetahuanku dan juga Belinda, Renata muncul dengan masih mengenakan seragam sekolah.
“Ayah, Ibu!” Berlari kecil Renata merangkulku, aku hanya terdiam.
Renata baru pulang sekolah. Dia baru tahu kalau aku tiba semalam lewat ibuku. Selama ini Renata tinggal bersama ibunya, di rumah orangtua Belinda. Namun setiap hari Renata selalu menemani ibuku yang juga adalah Omanya sendiri. Terkadang pula Renata nginap di situ. Ibuku sangat sayang pada cucunya, Renata.
“Oma, benarkah Ayah udah pulang?”
“Iya, semalam Ayahmu tiba. Tapi ayahmu langsung masuk tidur, mungkin dia capek!”
“Lalu di mana ayah sekarang, Oma. Aku belum ketemu dengan Ayah!”
“Tuh, di kantin sana, ngobrol sama teman-temannya!”
Renata bergegas dengan luapan hati yang gembira. Sebab kurang lebih tiga tahun dia tak pernah melihat aku lagi. Begitu pula sebaliknya aku.
Saat itulah Renata tiba-tiba muncul disaat aku sedang bersitegang dengan Belinda, ibunya.
“Ayah, ayo kita pulang, Ibu, ayo bu, kita pulang!”
Renata menarik tanganku dan ibunya Belinda.